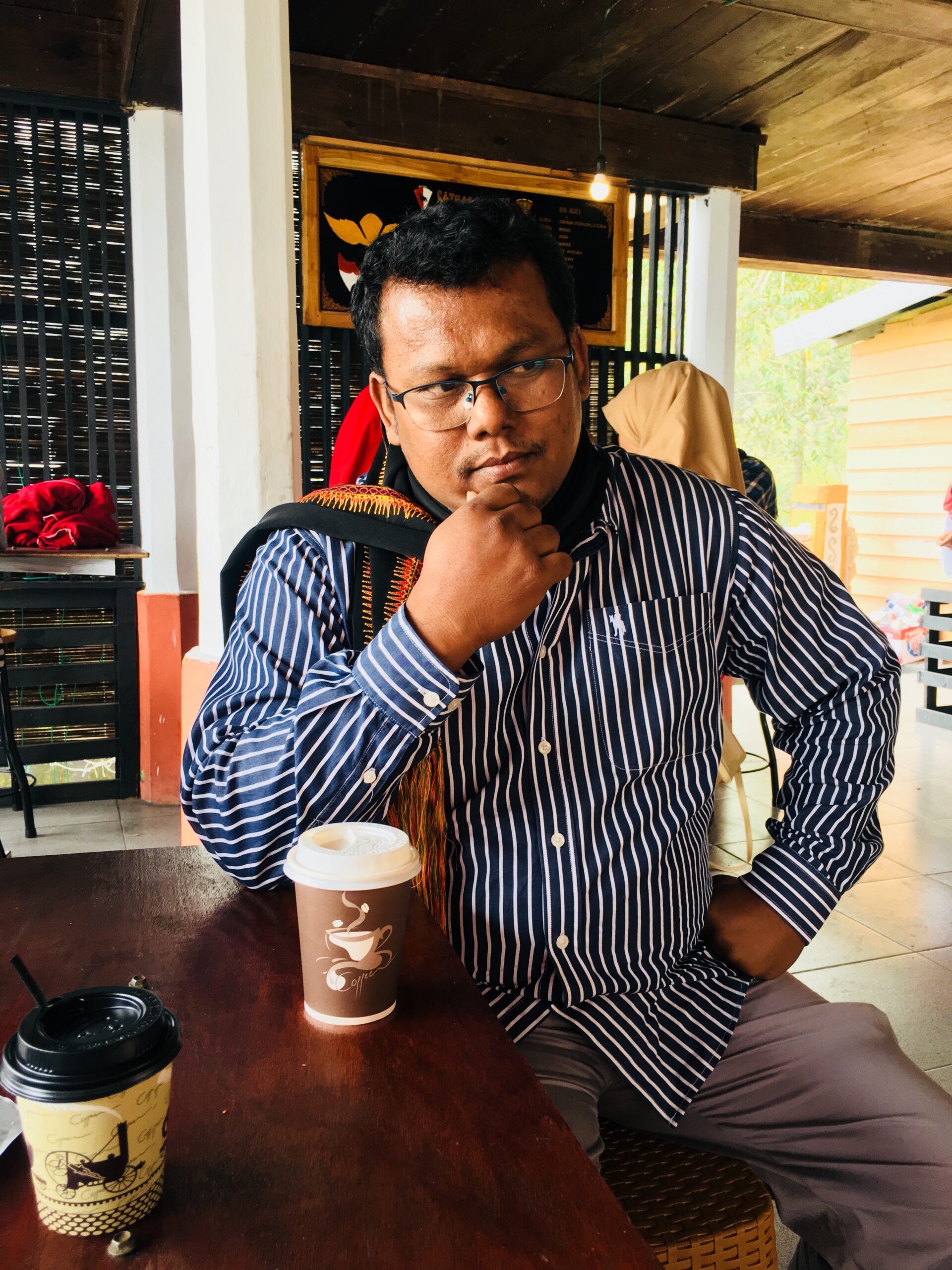Oleh: Ari J. Palawi
Dalam kehidupan masyarakat Aceh hari ini—baik di kampung maupun di perantauan—kita sering dihadapkan pada dilema: mana yang lebih sahih dan pantas diikuti, adat yang diwariskan oleh ureung tuha, atau syariah yang dibawa oleh negara? Banyak yang melihat adat sebagai warisan lama yang mulai usang, dan syariah sebagai sistem hukum modern yang lebih “resmi” dan bernilai agama. Tapi bagaimana jika pandangan itu keliru sejak awal? Bagaimana jika Aceh—jauh sebelum republik berdiri dan sebelum syariat diatur dalam qanun—sudah punya sistem hukum yang berakar pada nilai Islam, berbasis pada kearifan lokal, dan berfungsi sebagai dasar tata kelola masyarakat yang adil dan bermartabat?
Di sinilah letak pentingnya sebuah peribahasa Aceh kuno yang sarat makna:
“Adat bak Po Teumeureuhôm; Hukôm bak Sjiah Kuala; Meudjeulih Kanun bak Putroë Phang; Resam bak Bentara.”
Secara umum, artinya: Adat berada di tangan Sultan, hukum berada pada ulama besar Syiah Kuala, aturan sosial ditetapkan oleh Putroë Phang, dan resam atau tradisi dijaga oleh Bentara.
Penting dicatat, di Aceh adagium yang sering kita dengar ialah: “Adat ngon agama lagee zat ngon sifeut”—adat dan agama itu ibarat zat dan sifat, tidak bisa dipisahkan. Bukan sekadar slogan, ini adalah kerangka teologis dan sosiologis yang mendasari hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Aceh.
Dalam pengertian ini, Hadih Maja bukanlah sekadar warisan budaya. Ia adalah kerangka normatif yang hidup, diwariskan secara turun-temurun, dan tetap dipraktikkan dalam berbagai konteks hingga hari ini—dari mediasi tanah adat di kampung, pidato pejabat adat, hingga kurikulum pendidikan muatan lokal di sekolah-sekolah Aceh.
Hukum Aceh Itu Tidak Tunggal, Tapi Bertingkat dan Berlapis
Hadih Maja memperlihatkan kepada kita bahwa Aceh tidak menganut sistem hukum tunggal sebagaimana lazimnya negara modern yang hanya mengenal satu sumber hukum—yakni hukum negara yang tertulis dan formal. Sebaliknya, dalam tradisi Aceh, hukum disusun secara berlapis, dialogis, dan saling melengkapi, dengan pembagian otoritas yang adil dan fungsional antar berbagai tokoh dan lembaga masyarakat:
Adat berada di tangan Po Teumeureuhôm (Sultan): Ini bukan sekadar simbol kekuasaan. Raja Aceh dahulu menjadi penjaga dan pelindung tatanan sosial yang disebut Adat Mahkamah. Melalui titah dan wewenangnya, raja mengatur perdagangan, perang, tata kota, pajak, dan etika masyarakat. Adat di sini adalah kerangka besar kehidupan publik, tempat semua warga hidup dalam kehormatan, bukan paksaan.
Hukôm (hukum Islam) dipegang oleh Sjiah Kuala, ulama besar bernama Abdurrauf al-Singkili, yang menyesuaikan hukum fikih mazhab Syafi’i dengan kenyataan hidup orang Aceh. Ia menerjemahkan kitab-kitab hukum ke dalam bahasa Melayu, dan menjembatani antara syariat dan adat lokal. Dengan demikian, hukôm bukan hukum yang asing, tapi hukum yang membumi.
Kanun disusun oleh Putroe Phang, permaisuri Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Pahang. Ia dikenal dalam sejarah lisan sebagai penyusun tata aturan tentang pergaulan, pernikahan, etiket perempuan, arsitektur istana, hingga tata cara menjamu tamu. Di sini kita melihat peran perempuan Aceh yang sangat sentral dalam produksi hukum dan etika, jauh melampaui stereotip patriarkis yang sering melekat pada narasi hukum Islam.
Resam dijaga oleh Bentara, yaitu juru bicara istana dan pelaksana adat dalam bentuk yang hidup—melalui pantôn, syair, upacara, dan peringatan-peringatan adat. Resam adalah wajah hukum yang paling akrab bagi masyarakat: kita mengenalnya dalam larangan membuka hutan tanpa izin, tata cara kenduri, hingga sanksi sosial terhadap perilaku tak senonoh. Bentara menyuarakan hukum, bukan dalam bentuk pasal-pasal, tapi melalui suara, ritus, dan rasa.
Dengan sistem seperti ini, hukum di Aceh tidak berhenti pada tulisan di atas kertas atau sidang di ruang pengadilan. Ia hidup dalam banyak bentuk:
Dalam nasihat teungku saat menyelesaikan sengketa keluarga,
Dalam pantôn dan hikayat yang dilantunkan saat kenduri laut atau maulid,
Dalam tarian Saman yang bukan hanya hiburan, tapi juga ekspresi nilai kolektif dan harmoni sosial,
Dan tentu saja, dalam tutur kata ureung tuha yang sejak kecil kita dengar di balai, meunasah, dan dapur.
Inilah yang disebut hukum yang hidup (living law), hukum yang tidak memaksa dari atas, tapi tumbuh dari bawah—dari hati nurani masyarakat. Hadih Maja bukan hanya puisi, tapi kerangka kerja sosial yang masih hidup dan mengatur kehidupan kita sampai sekarang—tanpa perlu paksaan negara atau ancaman aparat.
Adat dan Syariah: Bukan Lawan, Tapi Saudara Kandung
Di Aceh, kita sering dengar ungkapan bijak ini:
“Adat ngon agama lagee zat ngon sifeut” — Adat dan agama itu seperti zat dan sifat,
tidak bisa dipisahkan.
Ungkapan ini bukan hanya indah secara sastra, tapi juga dalam. Ia menggambarkan falsafah hukum Aceh yang sejak lama melihat adat dan syariah sebagai dua wajah dari satu kebenaran. Bukan dua kutub yang bertentangan, tapi dua sahabat lama yang saling menjaga keseimbangan hidup masyarakat.
Sejak masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), tatanan hukum Aceh telah dirancang untuk mengharmonikan adat dengan agama. Pada masa itu lahir Adat Meukuta Alam, kitab hukum adat istana yang mengatur urusan perang, perdagangan, perkawinan, sampai tata cara perjamuan. Tapi kitab itu tidak berdiri sendiri. Di waktu yang sama, Syiah Kuala (Abdurrauf al-Singkili), sebagai mufti kerajaan, menyusun tafsir hukum Islam yang membumi, yang bisa diterapkan di masyarakat Aceh tanpa mencabut akar adat mereka.
Ulama besar seperti Syiah Kuala tidak berkata, “buang adat, ganti dengan syariah.”
Mereka berkata, “kawinkan adat dengan syariah, agar masyarakat hidup teratur, adil, dan damai.”
Contohnya dalam hukum waris. Masyarakat Aceh mengenal peunulang dan sagoe teupat, sistem pewarisan dalam adat yang kemudian disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip fara’id (hukum waris Islam). Dalam hal sengketa keluarga, banyak persoalan diselesaikan melalui musyawarah adat bersama teungku dan keuchik, bukan langsung dibawa ke Mahkamah Syariah—karena solusi adat dinilai lebih damai, lebih menyentuh hati, dan menjaga marwah keluarga.
Bahkan dalam hal yang dianggap “modern” seperti qanun (peraturan daerah berbasis syariah), Aceh tetap menggunakan pendekatan adat. Banyak pasal dalam qanun jinayat misalnya, diinterpretasi ulang lewat forum tuha peut, atau dipadukan dengan prinsip maaf, damai, dan restitusi yang sudah lama jadi dasar dalam proses peusijuek (ritual perdamaian adat).
Dengan kata lain, adat tidak menyaingi agama, dan agama tidak menyingkirkan adat. Keduanya seperti air dan sungai: agama adalah mata air yang memberi nilai ilahiah, adat adalah sungai yang membentuk jalannya di tengah hutan sosial Aceh. Nilai Islamnya sama, tapi bentuk pelaksanaannya khas Aceh—dengan syair, dengan petuah, dengan penghormatan kepada ureung tuha.
Karena itu, orang Aceh tidak perlu bingung: mencintai adat bukan berarti menolak Islam. Sebaliknya, mempertahankan adat adalah bagian dari menjaga jatidiri keislaman kita yang penuh hikmah dan kelembutan.
Perempuan Itu Juga Pembentuk Hukum, Bukan Hanya Pengikutnya
Bagi masyarakat yang sering menganggap bahwa hukum adalah urusan laki-laki atau hanya wilayah ulama, Hadih Maja membawa pelajaran yang membebaskan sekaligus menantang. Mengapa? Karena di dalamnya disebut dengan tegas:
“Meudjeulih kanun bak Putroe Phang” — Penyusun aturan (kanun) adalah Putroe Phang, seorang perempuan.
Ini bukan dongeng istana.
Ini bukan simbol hiasan dalam sejarah.
Ini pengakuan konkret bahwa perempuan Aceh punya otoritas hukum.
Putroe Phang bukan sekadar istri dari Sultan Iskandar Muda. Ia adalah sosok yang bertanggung jawab atas kanun-kehidupan: aturan-aturan yang mengatur bagaimana rakyat hidup, bagaimana keluarga dibina, bagaimana etika dalam rumah tangga, dalam berpakaian, menerima tamu, hingga tata krama dalam masyarakat. Dengan kata lain, Putroe Phang adalah ahli tata negara dalam lingkup sosial dan moral. Dan masyarakat Aceh sejak dulu mengamini peran ini.
Warisan itu tidak mati. Sampai hari ini, kita melihat kelanjutannya dalam berbagai bentuk.
Misalnya, saat masa konflik bersenjata, banyak laki-laki mengungsi atau hilang. Tapi siapa yang mengambil alih ruang sosial dan menjadi penjaga martabat kampung? Inong Bale. Mereka bukan hanya memasak atau merawat anak. Mereka membentuk forum-forum perdamaian, menyusun aturan baru untuk melindungi hak perempuan, dan membangun solidaritas sosial yang mengobati luka-luka kolektif.
Hari ini, ibu-ibu di kampung—meskipun tanpa gelar sarjana hukum atau jabatan formal—masih sering menjadi rujukan dalam perkara warisan, sengketa tanah, masalah pernikahan, dan konflik keluarga. Mereka tidak membaca kitab fiqih di atas mimbar, tapi mereka membaca rasa keadilan lewat pengalaman, kehalusan hati, dan logika adat. Dan keputusan mereka sering lebih diterima, karena diucapkan dengan suara yang penuh hikmah dan kasih. Jadi kalau hari ini ada yang bilang perempuan tidak berhak bicara hukum, atau harus diam saat urusan syariah dibahas—maka Hadih Maja menjawab: “Itu bukan jalan Aceh.”
Di Aceh, hukum bukan hanya ditulis oleh pena ulama atau diputuskan oleh mulut lelaki,
tapi juga dibentuk oleh tangan ibu, lisan nenek, dan kebijaksanaan perempuan. Putroe Phang bukan satu-satunya. Sejarah mencatat nama-nama seperti Sultanah Tajul Alam Safiatuddin—perempuan pertama yang menjadi kepala negara Islam di Asia Tenggara; Cut Nyak Dhien—yang selain pejuang perang, juga pemimpin komunitas; dan para syarifah dan teungku inong di dayah-dayah yang mengajarkan hukum Islam dengan perspektif yang adil dan mendalam. Dengan semua ini, Hadih Maja mengingatkan kita: perempuan Aceh bukan pelengkap dalam hukum. Mereka adalah pemiliknya.
Pasca-Konflik dan Tsunami: Saat Adat Menjadi Sandaran Hidup
Setelah gempa bumi dan tsunami menghantam Aceh tahun 2004, dan di tengah proses damai yang dimulai tahun 2005, banyak dari kita menyaksikan sendiri: negara kewalahan, tapi masyarakat bergerak. Listrik padam, kantor-kantor lumpuh, aparat kebingungan. Tapi siapa yang pertama kali berdiri, memandu proses pemakaman massal, membagi logistik seadanya, dan menenangkan yang berduka?
Teungku di meunasah.
Keuchik di balai desa.
Pawang laut, Imum Mukim, dan tokoh adat.
Mereka tidak menunggu surat keputusan. Mereka tidak membaca undang-undang.
Mereka membaca tanda, membaca situasi, dan membaca hati orang kampung.
Dan yang mereka pegang bukan lembaran hukum dari Jakarta,
tapi ingatan kolektif—termasuk Hadih Maja, yang menjadi pedoman diam-diam tapi tegas.
Dalam banyak kasus, mahkamah adat dihidupkan kembali bukan karena instruksi pemerintah, tapi karena kebutuhan nyata:
Ada konflik tanah yang harus diselesaikan tanpa gaduh.
Ada masalah warisan yang butuh mediasi damai.
Ada anak-anak yatim yang perlu perlindungan kolektif.
Dan ketika situasi mulai tenang, Hadih Maja masuk ke sekolah-sekolah. Tapi kali ini bukan sekadar materi lomba cerdas cermat. Anak-anak diajak menghafalnya sebagai jati diri.
Mereka mulai memahami:
“Ooo, jadi selama ini hukum di Aceh itu bukan hanya yang dibacakan di pengadilan, tapi juga yang dinyanyikan di kenduri, yang dibisikkan oleh nenek, yang diucapkan oleh keuchik saat memisah dua yang berselisih.”
Di kampung-kampung, guru-guru mulai bertanya kepada siswa:
“Siapa Putroe Phang itu?”
“Apa arti hukôm bak Syiah Kuala?”
“Kenapa adat bukan sekadar kebiasaan, tapi dasar keadilan?”
Ini adalah kebangkitan kesadaran hukum dari bawah. Bukan hukum yang menakutkan rakyat, tapi hukum yang lahir dari rakyat. Hukum yang bisa dipegang, diingat, dan diteruskan—tanpa perlu gelar sarjana untuk memahaminya. Dan inilah kekuatan Hadih Maja. Bahwa ia bukan hukum yang dibacakan di atas mimbar kekuasaan, tapi hukum yang dihidupkan dalam hubungan antar sesama. Ia bukan produk lembaga tinggi negara, tapi warisan ureung tuha yang terus relevan dalam menghadapi zaman.
Aceh Tidak Perlu Menjadi Orang Lain untuk Menjadi Islami dan Adil
Hari ini, ketika Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan syariat Islam secara formal, sebagian orang merasa risau:
“Apakah adat akan hilang?”
“Apakah semua harus diganti dengan hukum kitab dan pasal?”
Kekhawatiran ini tidak datang dari luar, tapi dari hati kita sendiri—karena kita tahu bahwa selama ini, adat bukan penghalang agama. Justru sebaliknya: ia adalah tanah tempat syariah bertumbuh.
Dan di sinilah Hadih Maja memegang peran sentral. Ia mengingatkan kita bahwa orang Aceh tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi Muslim yang taat dan warga yang adil.
Kita tidak perlu meniru cara berpakaian orang Arab, cara berhukum orang Pakistan, atau cara mengatur negara seperti Timur Tengah.
Karena kita punya warisan sendiri:
Syiah Kuala yang menulis fikih dalam bahasa Melayu.
Putroe Phang yang menyusun kanun rumah tangga.
Bentara yang menyampaikan hukum lewat syair.
Sultan yang memimpin bukan dengan kekerasan, tapi dengan wibawa adat.
Itulah Aceh. Sebuah masyarakat yang menyatukan Islam dan adat seperti zat dan sifat.
Islam di Aceh tidak kaku dan menakutkan, tapi berirama, bermakna, dan bermartabat.
Ia hidup dalam kenduri, dalam zikir, dalam hukum warisan yang disepakati, dalam upacara perkawinan yang penuh simbol dan restu kolektif.
Justru ketika kita mencoba meniru luar—dengan mengebiri adat, membungkam suara teungku kampung, atau menyederhanakan hukum hanya dalam bentuk pasal-pasal kaku—di situlah keadilan bisa terputus dari akar.
Hadih Maja adalah perisai Aceh. Ia menjaga agar hukum tidak hanya sah di atas kertas, tapi juga adil di hati masyarakat. Ia menjadi bukti bahwa hukum bisa Islami tanpa menjadi asing, bisa tegas tanpa kehilangan kasih, bisa sakral tanpa kehilangan rasa.
Jadi, kalau ada yang bertanya:
“Aceh mau jadi negara Islam seperti siapa?”
Jawabannya jelas:
Aceh tidak mau jadi seperti siapa-siapa. Aceh cukup menjadi dirinya sendiri.
Karena sejak dulu, Aceh sudah Islami, sudah adil, dan sudah punya konstitusinya sendiri—dalam bahasa sendiri, suara sendiri, dan jiwa sendiri.
Hadih Maja: Warisan yang Masih Bernapas
Hadih Maja bukanlah peninggalan yang kaku, disimpan dalam museum atau ditulis di dinding balai. Ia adalah sesuatu yang hidup—yang kita dengar dalam rapai di pesta maulid, dalam pantôn di pesta adat, dalam saran diam-diam dari teungku kepada pasangan muda, dalam keputusan keuchik saat tanah diwariskan tanpa surat.
Ia hadir dalam suara, dalam nada, dalam suasana.
Bukan sekadar untuk dikenang—tapi untuk dijalani.
Di tengah tekanan zaman—dari birokrasi yang serba dokumen, hingga dakwah yang serba literal—warisan ini pelan-pelan bisa terlupakan. Tapi selama masih ada yang mengucapkannya, mengajarkannya, bahkan hanya mengingatkan bahwa “hukôm bak Syiah Kuala, adat bak Po Teumeureuhôm”, maka roh Hadih Maja belum pergi.
Ia bukan milik masa lalu.
Ia adalah napas panjang Aceh yang masih bersambung.
Boleh jadi hari ini, bentuknya berubah. Ia tidak lagi hanya dipelajari di meunasah, tapi juga dibahas dalam ruang kelas, dipentaskan di panggung seni, bahkan diangkat dalam diskusi kebijakan.
Tapi yang terpenting bukan bentuknya, melainkan nadinya: bahwa hukum di Aceh bukan hanya tertulis, tapi dirasakan; bukan hanya dikatakan, tapi dijalankan; bukan hanya mengatur, tapi juga mengingatkan kita siapa kita, dan bagaimana sebaiknya kita hidup bersama.
Dan selama itu masih ada—di bibir nenek, dalam tulisan guru, atau dalam langkah pemuda yang berani menyambungnya—maka Hadih Maja tetap menjadi bagian dari masa depan.
Bukan sebagai slogan, tapi sebagai ruh dari hukum yang beradab, berakar, dan bermartabat.