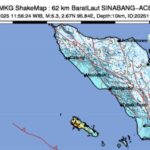Oleh: Ari J Palawi
Kita di Aceh terlalu sibuk bicara tentang syariat, investasi halal, dan geopolitik lokal. Tapi satu hal paling mendasar nyaris luput dari perhatian, yakni: bahasa ibu—bahasa daerah—diabaikan secara sistematis dan diam-diam. Tidak banyak yang sadar bahwa saat anak-anak Aceh tidak lagi bisa bertutur dalam bahasa orang tuanya, yang hilang bukan cuma bahasa, tapi cara hidup dan cara berpikir.
Bahasa Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Aneuk Jamee, bahkan bahasa Aceh sendiri—semuanya perlahan surut di tengah arus Bahasa Indonesia dan budaya global. Sekolah tak lagi menjadikan bahasa lokal sebagai bahasa pembentuk nalar. Rumah tangga pun ikut latah, seolah lebih modern bila berbicara dengan anak dalam bahasa nasional. Dan yang lebih menyedihkan, pemerintah daerah tampak nyaman saja dengan hilangnya semua ini.
Padahal, penelitian menyebutkan bahwa pendidikan yang dimulai dari bahasa ibu menghasilkan siswa dengan daya literasi lebih tinggi dan pemahaman konseptual lebih dalam (UNESCO, 2015). Di Aceh, studi oleh Mulyani et al. (2024) membuktikan bahwa guru-guru dasar dan menengah menyadari pentingnya bahasa daerah dalam pembelajaran, tetapi tidak punya dukungan struktural. Sayangnya, tidak ada pelatihan guru, tidak ada buku teks, bahkan tak ada ruang di jam pelajaran.
Dalam hal ini, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi alat berpikir dan membentuk logika. Clifford Geertz menyebut bahasa sebagai medium dari “worldview”—kerangka dunia sosial dan simbolik yang diinternalisasi lewat kata (Geertz, 1973). Jadi, saat bahasa lokal mati, kita bukan hanya kehilangan ekspresi budaya, tapi kehilangan lensa untuk memahami realitas dari sudut Aceh sendiri.
Kita sering mengklaim Aceh sebagai negeri yang penuh jati diri. Tapi faktanya, dalam praktik sehari-hari, tidak ada distribusi kebijakan yang adil terhadap seluruh komunitas bahasa di Aceh. Bahasa Aceh cenderung dominan dalam ranah publik—dari administrasi hingga media lokal—sementara bahasa lain seperti Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Kluet, dan Tamiang sering hanya dimunculkan dalam momen-momen seremoni atau festival budaya. Itu pun sekadar tempelan, bukan sebagai alat ekspresi hidup.
Syahputera et al. (2024) dalam telaahnya menyebut ketimpangan ini sebagai “ketidaksadaran linguistik”, di mana kebijakan kebudayaan gagal memahami bahasa sebagai modal rekonsiliasi pasca-konflik dan basis partisipasi warga. Jika hanya satu atau dua kelompok yang diberi ruang, yang lain akan merasa “tidak termasuk” dalam narasi Aceh kontemporer. Dan seperti yang kita tahu, rasa tak diakui adalah benih dari perpecahan yang lama.
Yang membuat keadaan lebih genting adalah bahwa hampir tidak ada kegelisahan publik soal ini. Tidak ada gerakan bahasa, tidak ada protes, bahkan tidak ada keingintahuan kolektif. Yang ada hanyalah diam. Bahasa lokal dibiarkan hilang secara perlahan, bahkan sering dengan restu diam-diam dari para elite—baik di pendidikan, pemerintahan, maupun adat.
Sementara itu, lingkungan publik kita makin asing dari bahasa lokal. Penelitian terbaru tentang lanskap bahasa di Peunayong (Sari et al., 2024) menunjukkan hanya 4% rambu toko menggunakan nama Aceh. Selebihnya memakai bahasa Indonesia dan Inggris. Itu bukan cuma gejala pasar, tapi cermin dari bagaimana kita memosisikan bahasa ibu dalam relasi nilai sebagai sesuatu yang “kampungan”, “jadul”, atau tidak punya nilai jual.
Bahasa ibu kini dipinggirkan bukan karena kalah dalam argumen, tapi karena tidak diberikan kesempatan untuk berbicara.
Dan kita semua diam. Pemerintah tidak bertindak. Sekolah tidak menyusun ulang. Akademisi enggan menulis. Media enggan bicara. Bahkan orang tua pun pelan-pelan mulai merasa asing dengan lidah sendiri. Kita menyaksikan proses pemutusan sejarah secara kolektif.
Padahal yang kita pertaruhkan bukan cuma bahasa. Tapi daya hidup, martabat, dan kemampuan Aceh membangun masa depan dengan fondasi budayanya sendiri.
Menyebut Tuhan dalam Bahasa Sendiri
Aceh pasca-konflik mestinya lebih arif.Kita sudah terlalu lama meletakkan martabat pada senjata, wilayah, dan otonomi fiskal. Tapi kedaulatan tidak hanya soal politik, melainkan juga kedaulatan budaya. Dan bahasa adalah inti dari itu. Jika bahasa tidak dianggap penting, maka seluruh mimpi tentang perdamaian dan kemajuan hanya jadi retorika yang mudah rapuh. Bahasa adalah jantung identitas.
Bahasa adalah cara seseorang merasa punya rumah.
Pendidikan formal kita, dari SD hingga madrasah, seolah tidak pernah sadar bahwa bahasa ibu adalah fondasi utama kecerdasan kultural dan moral anak-anak Aceh. Tidak ada pelatihan guru untuk mengajarkan bahasa daerah. Tidak ada buku bacaan anak yang hidup dalam bahasa Gayo, Aneuk Jamee, atau Aceh. Tidak ada kurikulum muatan lokal yang dirancang dengan serius, apalagi dibangun bersama komunitas. Yang ada hanyalah formalitas, sebatas mengisi lembar RPP tanpa ruh.
Sementara itu, di luar kelas, banyak orang tua di perkotaan dengan bangga berkata bahwa anaknya lebih nyaman berbahasa Indonesia. Mereka menyebut itu sebagai “kemajuan.” Padahal yang sedang terjadi adalah pemutusan jejak rasa, jejak sejarah, dan cara mencintai tanah air secara intim. Anak yang tak lagi tahu bagaimana menyebut “sayang” dalam bahasa ibunya akan tumbuh dengan kosakata kasih yang dingin. Anak yang tak paham metafora puisi daerahnya akan kesulitan menyentuh nilai terdalam dari peradaban tempat ia lahir.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
Kita tidak butuh lembaga baru yang sibuk menyusun piagam dan cetak baliho. Yang kita butuhkan adalah gerakan sadar—lintas sektor, lintas usia, dan lintas bahasa. Dayah dan pesantren bisa mulai dengan membacakan kembali hikayat dan syair-syair lama, bukan sebagai peninggalan, tapi sebagai pelajaran akal-budi. Sekolah-sekolah bisa membuat kelas tambahan bahasa lokal seminggu sekali, bahkan cukup 30 menit—asal dilakukan dengan cinta dan konsistensi.
Kita butuh anak-anak muda yang membuat podcast dalam bahasa ibunya, membuat sketsa lucu atau kisah horor berbahasa daerah, membuat game edukatif dalam dialek tempatan. Kita butuh pemerintah yang berani menganggarkan program revitalisasi bahasa bukan sebagai beban, tapi sebagai investasi peradaban.
Bahasa ibu adalah masa depan, bukan karena kita ingin memutar waktu ke masa lalu, tapi karena kita ingin masa depan yang tidak kehilangan ingatan.
Bayangkan satu generasi Aceh yang tumbuh dalam pendidikan dwibahasa—fasih dalam bahasa global, tapi tetap berpikir dalam bahasa daerah. Mereka bisa jadi pemrogram komputer yang menyisipkan nilai lokal ke dalam desain aplikasinya. Mereka bisa menulis jurnal ilmiah sekaligus menulis puisi dalam dialek ibunya. Mereka bisa mendunia tanpa kehilangan kaki tempat berpijak.
Bayangkan jika di tahun-tahun mendatang, ada siswa SMK yang membuat kamus daring Aceh-Gayo-Singkil. Ada pelajar pesantren yang menghidupkan kembali seni tutur Pho atau Didong lewat AI. Ada ruang kelas yang membuka pelajaran sains awal dalam bahasa ibu agar anak memahami ilmu bukan dari kosa kata asing, tapi dari istilah yang telah hidup di sekitarnya selama ratusan tahun.
Di tengah dunia yang semakin didikte oleh algoritma global dan logika pasar, bahasa ibu adalah ruang perlindungan dan perlawanan. Ia menyimpan rasa yang tak bisa dijelaskan oleh emoji, menyimpan puisi yang tak bisa dikompres jadi caption. Ia adalah bentuk kesetiaan pada akar, tanpa menolak kemajuan.
Dan kalau kita tidak bertindak hari ini, maka yang hilang bukan cuma bahasa. Yang akan hilang adalah cara kita menyebut cinta, menyebut tanah, menyebut Tuhan—dalam bahasa yang paling dekat dengan batin kita sendiri.
Karena pada akhirnya, siapa kita tanpa bahasa kita sendiri?
Tentang Penulis:
Ari Palawi adalah peneliti dan pendidik di bidang seni, budaya, dan masyarakat di Universitas Syiah Kuala. Ia aktif menulis tentang relasi budaya, Islam, dan peradaban lokal. Menyelesaikan studi di Banda Aceh, Hawai‘i, dan Australia, ia terus belajar dari masyarakat akar rumput dan para ulama yang menjaga warisan dengan hati.